Epistemologi Islam Berkemajuan
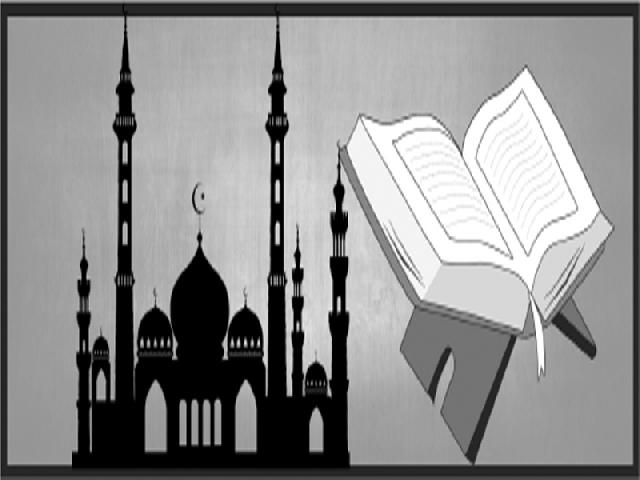
Gagasan "Islam berkemajuan" sejak awal sudah mengundang kritik, sebagaimana juga gagasan "Islam Nusantara." Padahal, pihak ketiga menganggap bahwa dua gagasan itu membentuk gagasan "Islam Indonesia", sebagaimana diartikulasikan oleh Profesor Syamsul Arifin yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara atau dengan "Islam Arab." Pengusung gagasan "Islam Nusantara", yaitu NU berpendapat bahwa Islam yang merangkul semua varian budaya nusantara itu, sebagaimana dikatakan KH Said Aqil Siraj, yaitu metode dakwah yang dibawakan oleh Wali Songo, telah membentuk toleransi perdamaian dan solidaritas kebangsaan sebagai syarat utuk mencapai kemajuan bangsa.
Sedangkan, Islam berkemajuan, yang adaptif dan akomodatif terhadap setiap kemajuan zaman sebagaimana dikatakan oleh mantan ketua Muhammadiyah Din Syamsudin, akan menimbulkan dinamika masyarakat ke arah kondisi yang senantiasa lebih baik. Namun, gagasan "Islam Nusantara" yang merangkul semua varian budaya lokal itu telah dikritik, selain karena merupakan sinkritisme yang berlawanan dengan paham puritanisme, "Tauhid Murni" Ibn Taymiyah dan Mohammad bin Abdul Wahab yang dianut oleh Muhammadiyah, juga karena seolah-olah merupakan mazhab regional. Dalam kenyataan sejarah, dimanapun Islam akan selalu beradaptasi dengan budaya lokal. Namun, Islam itu sendiri bersifat universal, di manapun sama, dan tidak mengandung pemahaman atau mazhab yang berbeda secara regional.
Sedangkan, "Islam Berkemajuan" memperoleh kritik karena seolah-olah Islam itu tidak sempurna sehingga sebagai doktrin komprehensif, masih perlu ditambah dengan gagasan "berkemajuan" dari luar, khususnya dari Barat. Padahal, menurut pembawa kritik itu, Islam itu sendiri adalah agama yang sesuai untuk segala zaman dan tempat. Dengan perkataan lain, Islam itu sendiri telah dan selalu modern. Namun, dalam kenyataannya, umat Islam itu pada umumnya berada dalam kondisi kemunduran, didera oleh kebodohan, kemiskinan, dan kemandekan (stagnasi). Karena itu, Islam itu sendiri sebagai suatu doktrin komprehensif memerlukan proses modernisasi.
Proses modernisasi telah terjadi di dunia Islam sejak awal abad-20. Pelopor modernisasi di dunia Islam adalah Muhammad Abduh, dalam bentuk penerimaan ilmu pengetahuan modern sesuai dengan ajaran Islam yang diikuti keharusan pendidikan ilmu pengetahuan modern. Namun, dalam kenyataannya, penerimaan ilmu pengetahuan modern itu diwujudkan dalam bentuk legitimasi teologis bahwa gagasan ilmu pengetahuan modern itu sudah terkandung dalam Alquran itu sendiri dan Alquran dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sikap akomodatif itu perlu dipahami berkaitan dengan tuduhan modernisasi Eropa bahwa Injil itu bertentangan dan menghambat ilmu pengetahuan.
Tetapi, umat Islam dalam realitasnya justru tidak pernah menghasilkan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Paling-paling umat Islam mengklaim penciptaan disertai dengan tujuan bahwa Eropa telah mencuri ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kejayaan Islam Abad Pertengahan. Modernisasi Muhammad Abduh sebenarnya bersumber dan berakar pada "the idea of progress" masa Pencerahan Eropa abad 19 yang diperolehnya ketika Abduh bermukim di Prancis dan menerbitkan majalah al Urwatul Wustha. Awal gagasan berasal dari pemikiran Francis de Fontenalle yang berpendapat bahwa kemajuan itu terkandung dalam karya kreatif yang terdapat pada kesenian dan ilmu pengetahuan Eropa. Filsuf Revolusi Prancis, Voltaire, menemukan esensi gagasan kemajuan pada rasionalisme. Sedangkan, filsuf puncak Pencerahan, Emmanuel Kant, melihat gagasan kemajuan pada kebebasan berpikir yang terlepas dari dominasi kekuatan di luar kemanusiaan, khususnya dogma keagamaan.
Gagasan Kant inilah yang merupakan sumber dari gagasan sekularisme yang memisahkan ilmu pengetahuan dari doktrin keagamaan. Ketika bangsa-bangsa Eropa bermigrasi ke benua baru Amerika, gagasan kemajuan yang terdapat dalam nilai atau doktrin kebebasan berkembang menjadi gagasan mengenai kemerdekaan (independence), republikanisme atau pemerintahan oleh publik yang berarti juga kepemimpinan yang dipilih oleh publik, serta demokrasi atau kedaulatan rakyat. Modernisme Islam memang menerima ilmu pengetahuan sebagai gagasan kemajuan. Tetapi, modernisasi Islam tidak meninggalkan ajaran agama, bahkan membuktikan bahwa gagasan kemajuan itu sendiri, misalnya, penggunaan akal pikiran, termasuk dalam pemahaman iman, terkandung dalam Alquran, sebagaimana terkandung dalam QS An Nahl (16): 125. Rasionalitas itu sendiri dalam Alquran terkandung dalam ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda yang terdapat dalam hukum-hukum yang terkandung dalam alam semasta (QS Al Baqarah (2): 129-130).
Dari segi epistemologi, filsuf Arab Maghribi, dari Maroko, Mohammad Abied al Jabiri, mengemukakan tiga pendekatan atau metode dalam epistemologi atau nalar Arab Islam. Pertama dan terutama adalah pendekatan al Bayani atau interpretasi terhadap teks wahyu. Kedua, pendekatan al Burhani atau pendekatan rasional dengan mempergunakan ilmu pengetahuan. Dan ketiga, metode al Irfani, yaitu metode yang berasal dari pengalaman hidup spiritual yang membentuk perilaku. Metode al Bayani memang mendatangkan salah pengertian. Metode ini dianggap sebagai wujud "kemalasan berpikir", yang hanya mengklaim kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat terkandung dalam ajaran Islam. Metode al Baysni seharusnya menjadi motif untuk menciptakan kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Motif ini terkandung dalam ayat-ayat yang menyuruh menggunakan akal dan ilmu. Di sini pendekatan al Bayani sejalan dan berintegrasi dengan pendekatan al Burhani. Pendekatan al Irfani terjadi apabila berbagai motif yang terkandung dalam Alquran sudah menjadi etos kerja kaum Muslimin.
Gagasan demokrasi atau kedaulatan rakyat terkandung dalam QS Ali Imran (3): 104, yaitu dalam pengertian al Ummah, sebagai landasan berpikir yang tidak hanya bisa diinterpretasikan sebagai masyarakat atau komunitas, tetapi juga sebagai organisasi atau institusi semacam negara atau lembaga civil society. Semua institusi itu dianjurkan oleh Alquran hendaknya didirikan oleh sebagian anggota masyarakat yang berkepentingan yang mengacu pada nilai-nilai keutamaan (al khair atau virtue). Sedangkan, republikanisme dapat ditafsirkan pada pengertian al Shura, sebagai demokrasi deliberatif. Tetapi, dari pendekatan al Bayani, gagasan kemajuan dalam Alquran itu terkandung dalam istilah-istilah al khilafah (QS al-Baqarah [2]: 30-33) dan QS Hud (11): 61 dan beberapa ayat lain mengenai kekhalifahan yang menunjukkan prinsip kedaulatan manusia atau kedaulatan rakyat di suatu negara atau komunitas dalam pengelolaan bumi untuk menciptakan kesejahteran.
Al amanah (QS al-Ahzab [33]: 72), yaitu kepercayaan (trust) bahwa manusia yang memikul kepercayaan itu akan melestarikan bumi, al adl atau keadilan (QS an-Nisa' [5]: 58 dan QS al-Maidah [6] 8) sebagai kerangka sadar pengelolaan sumber daya secara lestari dan berkelanjutan. Al shura atau musyawarah (QS Ali Imran [3]: 159 dan as-Shura [42]: 38), sebagai prinsip kepemimpinan dan metode pemecahan masalah masyarakat, al mizan (QS al-Mu'minun: 102, 103) asas kesetimbangan sebagai ukuran atas perbuatan baik dan buruk, al washatan, (QS al-Baqarah [2]: 143), yaitu modernisasi untuk menghindarkan konflik, al ukhuwah (QS al-Hujurat [49]: 10) yang menganjurkan solidaritas, persaudaraan dan kekeluargaan (fraternity atau brotherhood) dan taaruf (QS al-Hujrat (49): 13), yaitu saling pengertian antar suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat majemuk.
Kesemua nilai keutamaan itu adalah orientasi sebagai kerangka dasar tata kelola masyarakat modern yang lebih lengkap dan komprehensif dari gagasan kemajuan Eropa dan Amerika Utara. Dengan demikian, ditinjau dari segi epistemologi, gagasan "Islam berkemajuan" tidak perlu berorientasi pada the idea of progress Barat, tetapi secara autentik bersumber dari ajaran Alquran sendiri. ***
*) Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
